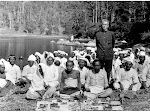|
| Oleh: M. Zaki Mubarak* |
Opini - Usainya hajatan Demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember lalu, menyisakan sejumlah catatan penting. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang umumnya disambut dengan antusias dan gembira, Pilkada kali ini justru dibayang-bayangi oleh kecemasan publik yang sangat kuat, di bawah ancaman pandemi covid-19 yang kian mengganas.
Pemerintah tetap bersikukuh pilkada untuk tetap dilangsungkan. Hingga Minggu 13/12/2020 Covid-19 sudah merengut nyawa lebih 18.600 orang, Jumlah korban yang tidak kecil tentunya. Hingga menjelang hari H pilkada, beberapa daerah menaikkan statusnya ke dalam zona merah yang menandakan darurat covid yang makin serius. Tampaknya, di mata pemerintah, penundaan yang berkepanjangan dikhawatirkan akan melahirkan sejumlah disfungsi yang sistemik yang berefek pada gangguan jalannya roda pemerintahan. Maka, the show must go on dengan segala konsekuensinya.
Kita tentu saja tidak menafikkan arti penting pilkada ini. Demokrasi lokal ini bagaimanapun merupakan buah dari reformasi ini yang diperjuangkan dengan susah payah. Banyak yang berharap akan muncul pemimpin-pemimpin di daerah yang lebih akuntabel dan responsif karena berasal dari suara arus bawah.
Beda dengan sebelumnya yang berdasar penunjukkan, sehingga kepala daerah hanya merasa perlu tanggungjawabnya kepada “Pemberi Petunjuk”, bukan pada rakyatnya. Dengan legitimasi lebih kuat –karena hasil pilihan langsung - perannya juga diharapkan semakin menentukan, setidaknya secara teoritis menjadi lebih otonom sebagai decision maker di daerahnya.
Pusat tidak lagi seenaknya melakukan intervensi atau ‘cawe-cawe’. Melalui pilkada yang demokratis pula, terbersit optimisme praktik-praktik korupsi yang dahulu menggila dan serta kejahatan politik lain akibat kekuasaan yang sentralistik akan mampu diminimalisir dengan tampilnya figure-figur gubernur, bupati dan walikota yang hebat plus berintegritas. Begitu besar dan mulia harapannya. Tetapi setelah menyaksikan sendiri setengah dasawarsa pilkada langsung berjalan, sejak 2005 hingga 2020 saat ini, akankah kita masih tetap optimis?
Kemerosotan Demokrasi
Jika proses politik di daerah kita anggap sebagai salah satu cerminan dari dinamika makro politik di level nasional, situasinya memang kurang menggembirakan. Bagi beberapa ahli yang secara intens mencermati perkembangan politik dalam negeri, nasib Indonesia saat ini seperti tengah ditakdirkan berada dalam lubang hitam kutukan.
Merujuk pada Freedom House, sejak 2017 hingga 2019, indeks kebebasan sipil dan politik di Indonesia terus merosot. Skala penurunan juga berjalan kian membesar. Pada 2018-2019 pointnya merosot dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya: dari angka 6.5 ke 6.4 (tahun 2017 ke 2018) kemudian terjun dari 6.4 ke 6.2.
Entah bagaimana dengan release 2020 nantinya, tapi nada-nadanya tampak semakin terjerambab mengingat makin bertambah kekacauan dan keruwetan negeri ini, Meskipun gambaran umum dukungan rakyat terhadap demokrasi masih cukup baik – setidaknya jika dibanding negara-negara lain di Asia, Afrika dan Arab yang bagian besarnya masih dikuasai rejim-rejim otoriter-, tapi terjadi penurunan meski tidak begitu besar.
Beda halnya dengan kepercayaan terhadap aktor-aktor demokrasi seperti politisi, partai politik, dan parlemen yang dari tahun ke tahun selalu saja berada pada titik yang rendah. Krisis kepercayaan ini bukan disebabkan oleh akibat meningkatnya ekspektasi atau harapan publik seperti terjadi di negara-negara demokrasi maju dewasa ini (Dalton, 2007), tetapi pada aktifitas dan kinerja aktor-aktor demokrasi yang memang semakin lama tambah semakin rusak (political decay).
Partai-partai politik kain terjerambab dalam politik kartel, bersama-sama sibuk memburu rente dan mengejar kepentingannya sendiri. Ideologi dan platform yang mestinya menjadi pembeda makin meluntur. Paralel dengan itu konsolidasi di level elite kekuasaan bukan untuk memperkuat demokrasi tetapi justru kian tegas arahnya kepada pengorganisasian oligarki politik.Semuanya itu makin bertambah suram dengan tingkah laku pemerintah yang belakangan cenderung makin repressif dalam menghadapi lawan politiknya.
Kembalinya Politik Feodal
Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu idealnya akan memberi kontribusi yang signifikan makin kuat dan tersebarnya demokrasi (spreading of democracy) di banyak daerah. Tentu saja kita berharap tidak hanya demokrasi teknis-prosedural tetapi jenis demokrasi yang hakiki atau substantif. Adagium demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat” dijunjung tinggi melalui pergiliran kekuasaan yang mencerminkan kehendak rakyat.
Jangan lupa, pergiliran kekuasaan ini sangat esensial dalam demokrasi –telah dipraktikkan sejak demokrasi kuno di Yunani- tapi dengan catatan: kompetensi dan integritas menjadi persyaratan yang melekat. Marwah dan nilai-nilai utama (virtues) demokrasi, seperti otonomi, kekebasan, tanggungjawab, keadilan, harus dijaga melalui aturan main yang accountable.
Dengan menyimak secara seksama perkembangan politik semakin kita mafhum bahwa apa yang tertulis di atas kertas, yang menjadi harapan bersama, tidak selalu paralel dengan realisasinya. Seperti itu yang akan banyak ditemukan jika kita coba mengkorelasikan antara demokrasi dengan pilkada di negeri ini, baik segi pelaksanaan maupun implikasi-implikasinya. Berbagai kontradiksi dan ketidaksinkronan terjadi di mana-mana.
Berbagai keanehan dalam proses pilkada membuat kita dapat memahami munculnya kekecewaan demi kekecewaan dari mereka yang megimpikan surga demokrasi di bumi Indonesia . Tanpa menafikkan segi-segi positifnya, terdapat catatan-catatan kritis terkait praktik pilkada yang belakangan justru semakin mempertontonkan banyak sisi gelapnya.
Pertama, menguatnya politik kekerabatan. Sungguh ironi bahwa laju perjalanan demokratisasi yang seharusnya telah terkonsolidasi, tingkatan aman dari semua unsur yang akan merongrongya, harus berjumpa dengan sejenis konsolidasi lainnya yang bersifat feodal. Salah satu diantaranya: mobilisasi politik berbasis kekerabatan yang pada pilkada 2020 tampil terang benderang, tidak lagi malu-malu. Negara Institute mencatat terdapat 124 calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik. Jumlah ini naik tajam hampir 2 kali lipat dari pilkada-pilkada sebelumnya. Ternyata, dari jumlah124 itu terdapat 29 diantaranya adalah istri-istri dari kepala daerah atau petahana yang berkuasa sebelumnya.
Kedua, politik lawan “kotak kosong”. Terdapat 25 daerah yang peserta pilkada diikuti satu pasangan calon, dan karenanya hanya berhadapan dengan kotak kosong. Skenario calon tunggal versus kotak kosong ini umumnya hasil muslihat picik untuk mencegah kompetisi.
Dengan berbagai cara, antara lain memborong habis semua tiket dari partai-partai politik sehingga calon kompetitor lansgung tereliminasi jauh hari sebelum peluit pertandingan dibunyikan. Sebagian lagi untuk mengakalinya –agar kelihatan lebih halus dan tidank menimbulkan kontroversi-. “calon boneka” dimunculkan sehingga seolah-olah ada lawan tanding sungguhan.
Maka, terjadilah apa yang disebut sebagai kontestasi palsu atau ‘a fake contest’ dimana masyarakat merasa di- fait accompli karena pilihannya jadi terbata, juga penuh rekayasa. Contoh yang paling gamlang adalah pilkada Solo yang melibatkan Gibran, putra Presiden Jokowi, yang setelah memborong parpol lalu dicarikan lawan dari orang awam yang sama sekali tidak dikenal sebelumnya.
What Next?
Masih banyak pekerjaan besar untuk meluruskan kembali jalan demokrasi yang mulai menceng ini menjadi lebih lurus dan rapi, juga untuk menambal bagian-bagiannya yang sudah bopeng. Untuk mengatasi persoalan kian menjalarnya feodalisme politik berupa “keluargaisme” atau “kerabatanisme” selain perlu gerakan yang lebih efektif di ranah legislasi dengan menghidupkan aturan main politik yang lebih reformis dan demokratis, juga memperkuat literasi politik di masyarakat.
Jika saja pelarangan politik dinasti tetap tercantum dalam regulasi tentu akan sangat baik, tapi kita masih ingat pada 2015 lalu Mahkamah Konstitusi (MK) dalam telah mencabut pasal larangan politik dinasti di dalam UU No 8 Tahun 2015. Hal ini bukan berarti semua celah telah tertutup. Bisa saja dalam revisi nantinya kembali disisipkan usulan pasal-pasal baru yang bunyinya mungkin tidak secara eksplisit melarang politik dinasti, namun dapat memberi efek mencegah atau setidaknya mempersulit kemunculannya.
Perjuangan lainnya yang juga strategis adalah mendorong komiten yang lebih kuat politisi dan partai-partai politik untuk menerapkan model seleksi kepemimpinan yang lebih demokratis berbasis kompetensi, prestasi dan integritas. Masih cukup banyak politisi-aktifis yang idealis di setiap parpol yang memiliki hasrat kuat terhadap refomasi internal kepartaian. Memperkuat jaringan diantara mereka dan mengotimalkan perannya untuk demokratisasi parpol menjadi modal sosial yang diperlukan bagi perbaikan demokrasi secara umum.
Yang tidak kalah pentingnya juga adalah edukasi kepada masyarakat itu sendiri Perlu waktu dan kesabaran untuk menumbuhkan adanya sikap warga negara yang kritis (critical citizens). Suatu elemen yang penting yang oleh Norris (2011) akan menopang survival demokrasi. Di mana masyarakat semacam itu selain mereka aktif dalam advokasi demokrasi, juga senantiasa kritis kepada pemerintah yang kebijakannya dinilainya keliru dan merugikan.
Proses edukasi terus menerus dengan membuka ruang-ruang diskusi partisipatif dan dialogis juga membantu terbentuknya political efficacy warga masyarakat. Tidak hanya mereka menjadi lebih melek politik tetapi juga punya kepercayaan diri yang tinggi bahwa suara dan tindakan mereka mampu membawa efek perubahan Bila saja hal-hal itu terwujud, kita akan menyaksikan semakin banyak rakyat yang tidak sudi bila aspirasinya dibeli ataupun dimanipulasi oleh para petualang politik yang rajin mengatasnamakan rakyat tetapi sesungguhnya hanya mengejar kepentingan pribadi, atau demi kerabatnya.
*Pengajar Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta